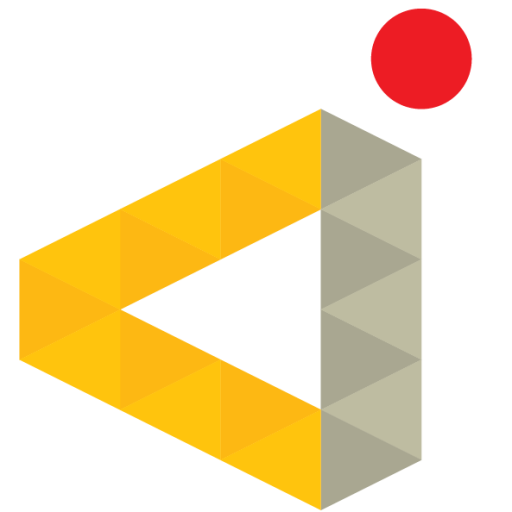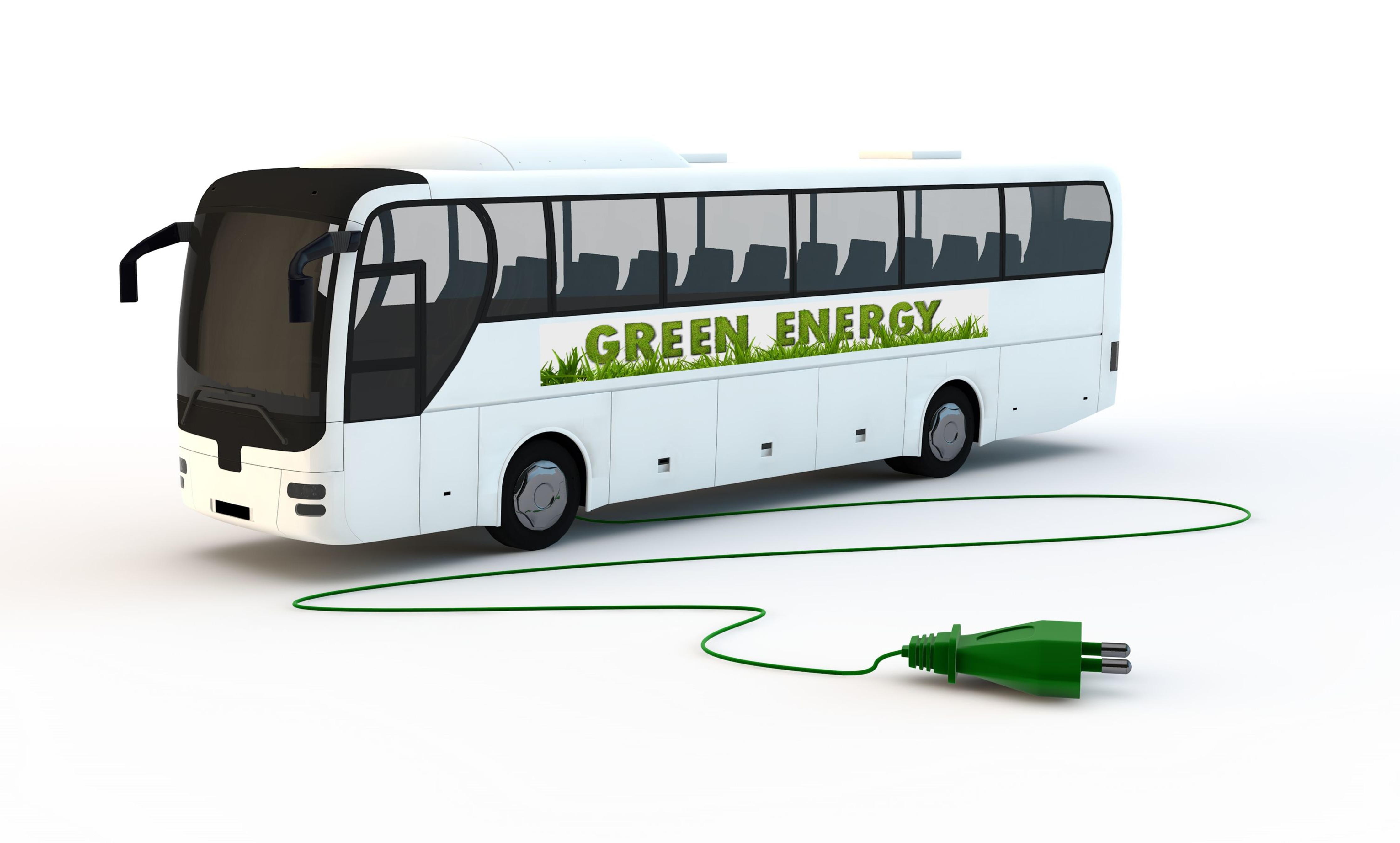Pajak Karbon Sebagai Alat Kebijakan untuk Mengatasi Perubahan Iklim: Implikasi dan Implementasi

Pemberlakuan pajak karbon akan dapat menekan laju peningkatan emisi sekaligus meningkatkan pendapatan suatu negara. Hal ini sudah dibuktikan oleh Finlandia dan Swedia. Bagaimana dengan Indonesia?
KOAKSI INDONESIA — Perubahan iklim yang disebabkan oleh peningkatan suhu bumi telah menjadi isu global. Aktivitas manusia yang masif dalam bidang industri, manufaktur maupun teknologi demi peningkatan ekonomi berakibat pada pemanasan global. Emisi karbon yang dihasilkan dari berbagai aktivitas tersebut menjadi penyebab utama perubahan iklim. Emisi karbon merupakan gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran berbagai senyawa yang di dalamnya terdapat karbon, misalnya CO2, solar, bensin dan bahan bakar fosil lainnya, ke lapisan atmosfer bumi.
Menurut laporan Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) 2022, Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara penghasil emisi karbon tertinggi. Sepanjang 2010—2018, emisi gas rumah kaca nasional mengalami peningkatan, yaitu sebesar 4,3% setiap tahun. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis. Pada 2016, Indonesia telah menandatangani Perjanjian Paris, yang menghasilkan kesepakatan Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai bentuk komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030 dengan kemampuan sendiri.
Salah satu kebijakan yang bisa diterapkan untuk merespons isu ini adalah pajak karbon. Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan atas setiap produk yang menghasilkan emisi karbon seperti bahan bakar fosil dan bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dengan cara memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk beralih ke sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.
Untuk mengimplementasikannya, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menjadi landasan hukum terkait pengaturan pemberlakukan pajak karbon. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa pajak karbon dapat dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Subjek dari pasal tersebut ialah orang perseorangan atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan kegiatan yang menghasilkan emisi karbon. Jadi, terdapat 2 objek yang menjadi sasaran yakni “pembelian barang yang mengandung karbon” dan “aktivitas yang menghasilkan emisi karbon”.
Lebih lanjut, pasal 13 ayat (8) menyatakan bahwa tarif pajak karbon harus ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon pasar per kilogram karbon dioksida ekuivalen yakni paling rendah sebesar Rp30,00 (tiga puluh rupiah). Penerimaan dari hasil pajak karbon tersebut dapat digunakan untuk pengendalian perubahan iklim dalam bentuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Dana yang dihasilkan akan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, mendukung investasi teknologi yang ramah lingkungan, serta untuk memberikan dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk bantuan sosial.
Melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pemerintah Indonesia secara resmi mulai menerapkan pajak karbon sejak April 2022. Pada awal penerapannya, Indonesia menetapkan pajak karbon atas sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara terlebih dahulu. Sektor ini dijadikan sebagai sektor percobaan untuk melihat pengaruh yang timbul dari pemajakan emisi karbon untuk kemudian diperluas ke sektor-sektor lain pada 2025. Perluasan pengenaan pajak karbon ke sektor-sektor lain akan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing sektor dan kondisi ekonomi Indonesia pada tahun tersebut.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani pada HSBC Summit 2022, ditundanya penerapan pajak karbon sampai 2025 disebabkan situasi ekonomi yang masih rentan dan belum sepenuhnya stabil setelah pulih dari pandemi COVID-19 serta adanya ancaman krisis pangan dan energi. Oleh karena itu, pemerintah masih terus melakukan perbaikan dan pengembangan baik terkait regulasi kebijakan maupun implementasinya agar nanti pajak karbon bisa terealisasi dengan baik. Penundaan juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi sektor-sektor yang akan dikenakan pajak karbon untuk melakukan penyesuaian dan persiapan.
Kebijakan pajak karbon ini telah diimplementasikan oleh beberapa negara. Finlandia dan Swedia merupakan contoh negara yang berhasil dalam menerapkan pajak karbon. Pemberlakuan pajak karbon di kedua negara ini mampu menekan emisi karbon sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka.
Data World Bank 2020 menunjukkan, Finlandia menjadi negara pertama yang menetapkan kebijakan pajak karbon pada 1990. Dalam kurun waktu 1990—1998, Finlandia berhasil menekan emisi karbon sebesar 7% dari total emisi yang dihasilkan. Kemudian, sejak 2000 hingga akhir 2018 emisi karbon Finlandia telah mengalami penurunan yang sangat signifikan yakni sebesar 19,49%. Pada 2013, Finlandia memperoleh tambahan penerimaan pajak sebesar US$800 juta dari pajak karbon. Sejak 20 tahun belakangan (2000—2020), Produk Domestik Bruto (PDB) Finlandia mengalami pertumbuhan sebesar 114%.
Negara kedua yang menerapkan pajak karbon adalah Swedia. Pada 1991, Swedia menerapkan pajak karbon terhadap bahan bakar fosil yang dipergunakan sektor-sektor penghasil emisi. Pemasukan yang diperoleh Swedia dari pajak karbon tersebut sebesar US$3,68 miliar pada 2013 yang naik US$1,3 miliar per tahun sejak 1993. Pada 2014, pajak karbon menyumbang PDB Swedia sebesar 7%. Sejak 1991 hingga 2018, Swedia telah berhasil menekan emisi karbon sebesar 27%, dengan penurunan terbesar terjadi di awal 2000.
Dari pajak karbon yang diterapkan tersebut, Swedia berhasil meredam kuantitas emisi karbon sekaligus mempertahankan dan memberi perlindungan terhadap kegiatan perekonomiannya. Berdasarkan data penerimaan pajak dari OECD (2019), Swedia berhasil mengumpulkan penerimaan pajak karbon sebesar US$2,3 miliar setara dengan 32,7 triliun rupiah pada 2019. Seluruh penerimaan dari pajak karbon ini masuk sebagai penerimaan pemerintah pusat tanpa dialokasikan ke hal-hal tertentu.
Indonesia pun akan memperoleh manfaat yang sama dengan Finlandia dan Swedia apabila menerapkan pajak karbon. Pemberlakuan pajak karbon hanya pada sektor energi sudah dapat meningkatkan pendapatan negara. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Bintang Adi Pratama, dkk, yang merupakan peneliti dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), penerimaan negara dari hasil pungutan pajak karbon dari sektor energi akan terus meningkat dari tahun 2019 sampai tahun 2025. Angka tersebut dihitung dengan tarif pajak karbon minimal yaitu Rp30.000 per ton CO2e. Diperkirakan pada tahun 2019 penerimaan negara bekisar Rp19,1 triliun, dan pada tahun 2025 penerimaan negara berkisar Rp23,6 triliun.
Contoh-contoh di atas memperkuat keyakinan kita bahwa kebijakan ini menjadi salah satu strategi penting bagi Indonesia dalam upaya transisi energi terbarukan secara bertahap untuk mengurangi emisi karbon sekaligus meningkatkan pendapatan negara.